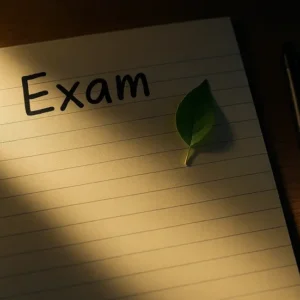Pengantar Memasuki Filsafat Ilmu
Pertemuan 2: Filsafat Ilmu
Pengertian dan Objek Ilmu
Ketika kita berbicara tentang ilmu, bayangan pertama yang muncul sering kali adalah tumpukan buku, laboratorium, atau para peneliti yang sibuk mengamati fenomena. Namun, ilmu sebenarnya lebih dari sekadar kumpulan data atau hasil eksperimen. Ilmu adalah sebuah usaha sistematis manusia untuk memahami dunia, alam, dan dirinya sendiri melalui metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara sederhana, ilmu dapat dipahami sebagai pengetahuan yang tersusun secara logis, konsisten, dan dapat diuji kebenarannya.
Dalam tradisi filsafat, ilmu didefinisikan bukan hanya sebagai “pengetahuan,” tetapi pengetahuan yang memiliki ciri khas tertentu. Menurut Jujun S. Suriasumantri (2017), ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri empiris, rasional, sistematis, dan universal. Artinya, ilmu tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi menuntut bukti yang dapat diamati, diolah dengan akal sehat, ditata dalam kerangka yang runtut, dan berlaku melampaui batas ruang maupun waktu. Visualisasinya bisa kita bayangkan seperti sebuah bangunan: pengetahuan sehari-hari adalah batu-batu yang berserakan, sementara ilmu adalah batu-batu yang disusun rapi membentuk tembok yang kokoh.
Lalu, apa yang dimaksud dengan objek ilmu? Objek ilmu dapat dibagi menjadi dua: objek material dan objek formal. Objek material adalah segala sesuatu yang menjadi bahan kajian ilmu, misalnya manusia, alam, masyarakat, atau gejala-gejala tertentu. Bayangkan seorang ilmuwan biologi yang meneliti tumbuhan; tumbuhan itu adalah objek material. Sedangkan objek formal adalah cara pandang atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam mempelajari objek material tersebut. Misalnya, seorang biolog melihat tumbuhan dari segi struktur dan fungsi, sementara seorang ekonom bisa melihat tumbuhan dari sudut pandang produksi dan distribusi hasilnya. Jadi, objek formal memberi arah dan membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya.
Secara sederhana, jika kita membayangkan dunia sebagai sebuah peta luas, maka objek material adalah seluruh peta itu sendiri, sedangkan objek formal adalah jalur yang kita pilih untuk menjelajahinya. Dengan demikian, ilmu tidak hanya tergantung pada “apa yang dipelajari,” tetapi juga “bagaimana cara mempelajarinya.”
Selain itu, ilmu memiliki fungsi praktis dalam kehidupan manusia. Pengetahuan ilmiah membantu kita memahami sebab-akibat dari suatu fenomena, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih rasional. Misalnya, ilmu kedokteran tidak hanya meneliti penyakit sebagai objek material, tetapi juga menggunakan metode ilmiah sebagai objek formalnya untuk menemukan cara pengobatan yang efektif.
Melalui ilmu, manusia bukan hanya berusaha menjelaskan realitas, tetapi juga menguasainya. Akan tetapi, penting diingat bahwa ilmu berbeda dengan kepercayaan atau dogma. Ilmu terbuka untuk diuji ulang dan dikritisi, sehingga sifatnya dinamis dan berkembang. Itulah sebabnya, dalam sejarah, ilmu selalu mengalami revisi dan penyempurnaan. Teori Newton tentang gravitasi, misalnya, kemudian diperkaya oleh teori relativitas Einstein.
Dengan memahami pengertian dan objek ilmu, kita dapat melihat bahwa ilmu bukan hanya sekadar kumpulan informasi, melainkan sebuah cara pandang, metode, dan sistem untuk menjelajahi realitas. Ia menuntun manusia agar tidak tersesat dalam pengetahuan yang berserakan, tetapi menyusunnya menjadi bangunan yang dapat menopang peradaban.
Referensi
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kaelan. Filsafat Ilmu: Telaah atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Chalmers, Alan. What Is This Thing Called Science? 4th Edition. Hackett Publishing, 2013.
Latar Belakang Filsafat Ilmu
Untuk memahami mengapa filsafat ilmu lahir, kita perlu menengok perjalanan sejarah manusia dalam mencari kebenaran. Pada mulanya, manusia hanya mengandalkan mitos, tradisi, dan kepercayaan turun-temurun untuk menjelaskan dunia. Misalnya, petir dianggap sebagai amarah dewa, atau penyakit dipahami sebagai kutukan. Namun, seiring berkembangnya akal budi, manusia mulai mempertanyakan: benarkah demikian? Dari sinilah lahir dorongan untuk mencari pengetahuan yang lebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Filsafat ilmu muncul sebagai refleksi atas proses tersebut. Ketika ilmu berkembang pesat—terutama sejak abad ke-17 melalui revolusi ilmiah yang dipelopori tokoh-tokoh seperti Galileo, Newton, dan Descartes—pertanyaan baru pun muncul: Apa yang membuat ilmu berbeda dari pengetahuan biasa? Apakah metode ilmiah benar-benar menghasilkan kebenaran? Bagaimana hubungan antara teori dan fakta? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lagi sekadar bersifat teknis, melainkan menyentuh aspek mendasar, sehingga membutuhkan kajian filosofis.
Di titik inilah filsafat ilmu hadir. Ia lahir dari kebutuhan untuk mengkaji fondasi ilmu itu sendiri. Jika ilmu ibarat sebuah rumah besar yang kokoh, maka filsafat ilmu adalah kegiatan memeriksa pondasi, pilar, dan arsitektur rumah tersebut: apakah sudah kuat, apakah ada celah, dan bagaimana rumah itu bisa bertahan dalam guncangan.
Dalam konteks Indonesia, Jujun S. Suriasumantri (2017) menjelaskan bahwa filsafat ilmu muncul karena adanya keraguan, keingintahuan, dan kebutuhan manusia untuk mencari kepastian. Manusia ingin tahu tidak hanya tentang “apa” yang diketahui, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” kita bisa mengetahui. Dengan kata lain, filsafat ilmu menjadi semacam cermin yang membantu ilmu melihat dirinya sendiri.
Secara historis, filsafat ilmu juga tidak terlepas dari perkembangan filsafat umum. Para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, sudah membicarakan perihal pengetahuan, kebenaran, dan metode berpikir. Namun, filsafat ilmu sebagai disiplin tersendiri baru tumbuh kuat pada abad ke-20, dengan munculnya filsafat positivisme logis, Karl Popper dengan falsifikasinya, hingga Thomas Kuhn dengan teori paradigma ilmiah. Perdebatan mereka menunjukkan bahwa ilmu tidak pernah netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh cara pandang, metode, bahkan konteks sosial.
Visualisasinya bisa dibayangkan seperti perjalanan seorang penjelajah. Ia telah memiliki peta (ilmu) yang menuntunnya menjelajahi dunia. Namun, suatu saat ia berhenti dan bertanya: apakah peta ini benar-benar akurat? Apakah simbol-simbolnya bisa dipercaya? Pertanyaan inilah yang membuat penjelajah tidak hanya menggunakan peta, tetapi juga meninjau kembali bagaimana peta itu dibuat. Itulah fungsi filsafat ilmu dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, latar belakang filsafat ilmu dapat dirangkum dalam tiga hal utama. Pertama, lahir dari kebutuhan manusia untuk mencari kebenaran yang lebih pasti daripada sekadar mitos atau opini. Kedua, muncul sebagai refleksi kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat. Ketiga, berfungsi sebagai pengawal agar ilmu tidak kehilangan arah, tidak terjebak pada klaim absolut, dan tetap terbuka terhadap kritik serta perubahan.
Referensi
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kaelan. Filsafat Ilmu: Telaah atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Popper, Karl. The Logic of Scientific Discovery. Routledge, 2002.
Positivisme Logis, Karl Popper, dan Thomas Kuhn
Sejarah filsafat ilmu pada abad ke-20 ditandai oleh perdebatan besar tentang bagaimana ilmu harus dipahami dan dijalankan. Dari sekian banyak aliran, ada tiga yang paling berpengaruh: positivisme logis, Karl Popper dengan teori falsifikasinya, dan Thomas Kuhn dengan konsep paradigma ilmiah. Ketiganya memberi warna tersendiri dalam cara kita memahami ilmu pengetahuan.
1. Positivisme Logis
Positivisme logis lahir dari Lingkaran Wina (Vienna Circle) pada tahun 1920-an. Para filsuf dan ilmuwan yang tergabung dalam kelompok ini—seperti Moritz Schlick, Rudolf Carnap, dan Otto Neurath—berusaha membangun ilmu yang bersih dari spekulasi metafisis. Mereka berpendapat bahwa hanya pernyataan yang dapat diverifikasi (dibuktikan secara empiris) yang bisa dianggap bermakna.
Bayangkan seorang peneliti berkata, “Ada kehidupan setelah kematian.” Bagi positivis logis, pernyataan itu tidak bermakna secara ilmiah, karena tidak bisa diverifikasi dengan pengalaman empiris. Sebaliknya, pernyataan “Air mendidih pada suhu 100°C pada tekanan normal” bisa diuji di laboratorium, sehingga sahih secara ilmiah. Dengan kata lain, positivisme logis ingin membatasi ilmu pada hal-hal yang dapat diobservasi dan diverifikasi.
Namun, aliran ini menghadapi kritik besar. Salah satunya adalah bahwa kriteria verifikasi ternyata sulit dipertahankan. Banyak teori ilmiah, seperti teori atom atau gelombang elektromagnetik, tidak bisa langsung diverifikasi, melainkan hanya melalui indikasi tidak langsung. Dari sinilah muncul kritik dari Karl Popper.
2. Karl Popper dan Falsifikasi
Karl Popper (1902–1994) menolak prinsip verifikasi. Menurutnya, ilmu tidak mungkin memastikan kebenaran mutlak dari sebuah teori, karena selalu ada kemungkinan teori itu salah di masa depan. Maka, ukuran keilmiahan bukanlah verifikasi, melainkan falsifikasi.
Popper mengibaratkan teori ilmiah seperti kapal yang mengarungi lautan: kapal itu tidak pernah benar-benar mencapai pelabuhan kebenaran mutlak, tetapi bisa terus diperbaiki agar lebih kokoh menghadapi badai kritik. Teori yang baik bukan yang bisa diverifikasi, melainkan yang bisa dibuka peluang untuk dibantah. Misalnya, teori “semua angsa berwarna putih” adalah teori ilmiah hanya jika kita mengakui kemungkinan munculnya angsa hitam yang membantah teori itu.
Dengan pendekatan ini, Popper ingin menegaskan bahwa ilmu bersifat kritis dan dinamis. Ilmu berkembang bukan karena membuktikan teori, melainkan karena berani menolak teori lama ketika terbukti salah.
3. Thomas Kuhn dan Paradigma Ilmiah
Thomas Kuhn (1922–1996) menambahkan perspektif baru yang lebih historis dan sosiologis. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions (1962), Kuhn memperkenalkan konsep paradigma. Paradigma adalah kerangka berpikir yang dianut oleh komunitas ilmiah pada suatu periode.
Menurut Kuhn, perkembangan ilmu tidak selalu berjalan linier atau akumulatif. Sebaliknya, ilmu mengalami “revolusi ilmiah.” Pada masa normal, ilmuwan bekerja dalam paradigma tertentu, misalnya paradigma Newtonian dalam fisika. Namun, ketika muncul terlalu banyak anomali (fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma lama), krisis terjadi. Akhirnya, paradigma lama digantikan oleh paradigma baru, seperti ketika teori Newton digeser oleh teori relativitas Einstein.
Kuhn menggambarkan ilmu seperti sebuah peta perjalanan kolektif. Selama peta itu bisa memandu dengan baik, ilmuwan akan menggunakannya. Tetapi ketika peta itu banyak menunjukkan jalan buntu, ilmuwan akan beralih ke peta baru. Proses ini bukan sekadar logika, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis, dan komunitas ilmiah.
Kesimpulan
Dari ketiga arus besar ini, kita bisa melihat perbedaan mendasar. Positivisme logis menekankan verifikasi empiris. Popper menekankan falsifikasi dan sikap kritis. Kuhn menekankan dinamika historis dan pergantian paradigma. Perdebatan mereka menunjukkan bahwa ilmu tidak pernah final, melainkan terus berubah sesuai kritik, konteks, dan perkembangan zaman.
Referensi
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kaelan. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
Pengertian Filsafat Ilmu
Setelah memahami apa itu ilmu dan bagaimana perkembangannya, pertanyaan yang wajar muncul adalah: apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Secara etimologis, istilah ini berasal dari dua kata, yaitu “filsafat” dan “ilmu.” Filsafat, sebagaimana dijelaskan sejak zaman Yunani kuno, berarti cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Ilmu, di sisi lain, merujuk pada pengetahuan yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka, secara sederhana, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji ilmu pengetahuan.
Namun, definisi sederhana itu baru langkah awal. Secara lebih mendalam, filsafat ilmu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang ilmu: Apa hakikat ilmu? Bagaimana ilmu berbeda dari pengetahuan biasa? Metode apa yang membuat suatu pengetahuan bisa disebut ilmiah? Dan apa tujuan ilmu bagi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan praktik ilmiah sehari-hari, melainkan perlu refleksi kritis dan sistematis.
Menurut Jujun S. Suriasumantri (2017), filsafat ilmu dapat dipahami sebagai refleksi filosofis atas dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu adalah upaya “menyelidiki penyelidikan.” Jika ilmu sibuk meneliti dunia dan fenomena, maka filsafat ilmu meneliti cara ilmu bekerja. Bayangkan sebuah kamera: ilmu adalah alat untuk menangkap gambar realitas, sementara filsafat ilmu adalah upaya memahami cara kerja kamera itu sendiri—lensa, cahaya, dan sudut pandang yang dipakai.
Kaelan (2010) menambahkan bahwa filsafat ilmu tidak berhenti pada pengertian teoretis, melainkan juga menimbang dimensi aksiologis atau nilai dari ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu tidak hanya menanyakan “apa” dan “bagaimana” tentang ilmu, tetapi juga “untuk apa” ilmu digunakan. Hal ini penting, karena ilmu yang tidak dikawal oleh refleksi filosofis bisa jatuh pada bahaya penyalahgunaan, seperti teknologi yang merusak lingkungan atau penelitian yang mengabaikan etika.
Dari perspektif sejarah, filsafat ilmu muncul karena kebutuhan untuk mengkritisi dan memberi fondasi pada ilmu yang berkembang pesat sejak revolusi ilmiah. Sebelum abad ke-20, pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu masih bercampur dengan filsafat umum. Baru setelah munculnya perdebatan besar tentang verifikasi, falsifikasi, dan paradigma ilmiah, filsafat ilmu berkembang sebagai cabang filsafat tersendiri.
Visualisasinya dapat digambarkan seperti sebuah rumah besar bernama “ilmu pengetahuan.” Para ilmuwan adalah penghuninya yang sibuk membangun ruang demi ruang. Tetapi filsafat ilmu adalah arsitek yang sesekali keluar, melihat keseluruhan bangunan, memeriksa pondasi, memastikan pilar tidak rapuh, dan bertanya: “Apakah arah pembangunan rumah ini masih sesuai tujuan semula?”
Dengan demikian, pengertian filsafat ilmu dapat dirangkum sebagai cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, metode, struktur, dan tujuan ilmu pengetahuan secara kritis dan reflektif. Ia menjadi semacam “cermin” yang membantu ilmu menilai dirinya sendiri. Tanpa filsafat ilmu, ilmu berisiko berkembang tanpa arah; sebaliknya, dengan filsafat ilmu, perkembangan ilmu tetap dalam jalur yang rasional, etis, dan bermanfaat bagi manusia.
Referensi
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kaelan. Filsafat Ilmu: Telaah atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Chalmers, Alan. What Is This Thing Called Science? 4th Edition. Hackett Publishing, 2013.
Objek Filsafat Ilmu
Setelah memahami pengertian filsafat ilmu, langkah berikutnya adalah menelaah objek kajiannya. Sama seperti ilmu pada umumnya yang memiliki objek material dan objek formal, filsafat ilmu pun demikian. Hal ini penting, karena tanpa memahami objek kajian, kita akan kesulitan menentukan arah dan batas pembahasan filsafat ilmu.
Secara umum, objek filsafat ilmu adalah ilmu itu sendiri. Jika ilmu mempelajari fenomena alam, sosial, atau manusia, maka filsafat ilmu menjadikan ilmu sebagai bahan refleksinya. Dengan kata lain, filsafat ilmu adalah “ilmu tentang ilmu.” Ia tidak meneliti tumbuhan, bintang, atau masyarakat, melainkan meneliti cara ilmu meneliti semua itu.
Objek filsafat ilmu dapat dibagi menjadi dua: objek material dan objek formal.
Objek Material Filsafat Ilmu
Objek material filsafat ilmu adalah seluruh pengetahuan ilmiah yang dihasilkan manusia. Semua bidang ilmu—fisika, biologi, sosiologi, kedokteran, hingga ekonomi—menjadi bahan kajian filsafat ilmu. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa berisi buku dari semua cabang ilmu. Filsafat ilmu tidak membaca isi tiap buku untuk mengetahui materi bidangnya, tetapi ia melihat keseluruhan koleksi itu: bagaimana buku-buku tersebut ditulis, disusun, dan apa pola yang mendasarinya.
Objek Formal Filsafat Ilmu
Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang khusus dalam mempelajari ilmu, yaitu refleksi kritis dan filosofis. Filsafat ilmu tidak sekadar mendeskripsikan teori ilmiah, tetapi bertanya: Apakah teori itu sahih? Apa kriteria kebenaran ilmiah? Bagaimana metode ilmiah bekerja? Untuk apa ilmu digunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini membedakan filsafat ilmu dari studi biasa tentang sejarah atau praktik ilmu.
Menurut Jujun S. Suriasumantri (2017), objek formal filsafat ilmu meliputi tiga dimensi utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
- Ontologi bertanya tentang hakikat objek ilmu. Misalnya, apakah objek ilmu hanya yang bisa diindera, ataukah juga hal-hal abstrak?
- Epistemologi mengkaji cara memperoleh pengetahuan ilmiah: metode apa yang digunakan, bagaimana hubungan teori dengan data, dan apa yang membedakan ilmu dari opini.
- Aksiologi membahas tujuan dan nilai guna ilmu. Apakah ilmu hanya untuk pengetahuan semata, atau harus memberi manfaat bagi kemanusiaan? Bagaimana dengan tanggung jawab etis seorang ilmuwan?
Jika divisualisasikan, filsafat ilmu ibarat seorang arsitek yang tidak hanya menilai kekuatan sebuah bangunan (ontologi), tetapi juga memeriksa cara pembangunan (epistemologi), serta mempertanyakan untuk apa bangunan itu digunakan (aksiologi).
Dengan demikian, objek filsafat ilmu tidak berhenti pada teori atau metode saja, melainkan mencakup seluruh aspek yang mendasari, membentuk, dan mengarahkan ilmu pengetahuan. Di sinilah peran penting filsafat ilmu: memastikan bahwa ilmu tidak hanya sahih secara metodologis, tetapi juga bermakna secara etis dan bermanfaat bagi manusia.
Referensi
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kaelan. Filsafat Ilmu: Telaah atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Chalmers, Alan. What Is This Thing Called Science? 4th Edition. Hackett Publishing, 2013.
Tujuan Filsafat Ilmu
Setelah memahami pengertian, objek, dan latar belakangnya, pertanyaan berikutnya adalah: untuk apa filsafat ilmu dipelajari? Mengapa kita tidak cukup hanya dengan mempelajari ilmu itu sendiri, tanpa harus merepotkan diri dengan refleksi filosofis? Jawaban atas pertanyaan ini membawa kita pada pemahaman tentang tujuan filsafat ilmu.
Secara sederhana, filsafat ilmu bertujuan untuk memberikan fondasi yang kokoh bagi ilmu pengetahuan. Ilmu berkembang pesat, menghasilkan berbagai teori, teknologi, dan penemuan. Namun, tanpa kerangka refleksi, ilmu bisa kehilangan arah. Filsafat ilmu hadir sebagai pengawal agar perkembangan tersebut tetap sahih secara metodologis, rasional, dan etis.
Menurut Jujun S. Suriasumantri (2017), tujuan filsafat ilmu mencakup tiga ranah utama:
1. Memberi kejelasan konseptual
Filsafat ilmu membantu kita memahami apa yang dimaksud dengan “ilmu,” apa bedanya dengan pengetahuan biasa, serta apa batas-batasnya. Dengan demikian, kita tidak terjebak dalam penyalahgunaan istilah, seperti menganggap mitos atau opini subjektif sebagai kebenaran ilmiah.
2. Mengkritisi metode ilmiah
Filsafat ilmu tidak puas hanya dengan menerima metode ilmiah apa adanya. Ia meneliti keabsahan, kelebihan, dan keterbatasan metode tersebut. Misalnya, apakah metode eksperimental dalam sains bisa berlaku untuk ilmu sosial? Atau adakah bentuk metode lain yang juga sahih?
3. Menimbang nilai dan tujuan ilmu
Filsafat ilmu mengingatkan bahwa ilmu tidak berdiri di ruang hampa. Ia selalu berkaitan dengan kepentingan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ilmu harus diarahkan pada kemaslahatan, bukan sekadar kepuasan intelektual atau kepentingan tertentu.
Kaelan (2010) menegaskan bahwa filsafat ilmu memiliki tujuan praktis dan normatif. Praktis, karena membantu ilmuwan dan masyarakat memahami cara ilmu bekerja. Normatif, karena memberi pedoman tentang bagaimana seharusnya ilmu digunakan. Dengan kata lain, filsafat ilmu bukan hanya teori, tetapi juga panduan moral dalam memanfaatkan pengetahuan.
Visualisasinya dapat digambarkan seperti sebuah kompas. Ilmu adalah kapal besar yang mengarungi lautan pengetahuan. Para ilmuwan adalah awak kapal yang sibuk mengoperasikan mesin, layar, dan peralatan. Namun, tanpa kompas, kapal bisa tersesat atau berlabuh di tempat yang salah. Filsafat ilmu berfungsi sebagai kompas yang memastikan kapal tetap menuju tujuan yang benar: kebenaran, kebermanfaatan, dan kemanusiaan.
Selain itu, tujuan filsafat ilmu juga mencakup dimensi pendidikan dan kesadaran kritis. Mahasiswa, peneliti, dan masyarakat luas diajak untuk tidak hanya menerima ilmu secara pasif, tetapi juga memahami, mempertanyakan, dan mengkritisinya. Dengan begitu, ilmu tidak diperlakukan sebagai dogma, melainkan sebagai pengetahuan yang selalu terbuka untuk penyempurnaan.
Akhirnya, tujuan filsafat ilmu adalah menempatkan ilmu pada posisinya yang tepat: sebagai sarana manusia untuk memahami dunia dan memperbaiki kualitas hidup, bukan sebagai alat kekuasaan atau dominasi. Dengan refleksi filsafat ilmu, kita diingatkan bahwa setiap pengetahuan membawa tanggung jawab.
Referensi
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- Kaelan. Filsafat Ilmu: Telaah atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Bakker, Anton & Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hardiman, F. Budi. Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Chalmers, Alan. What Is This Thing Called Science? 4th Edition. Hackett Publishing, 2013.